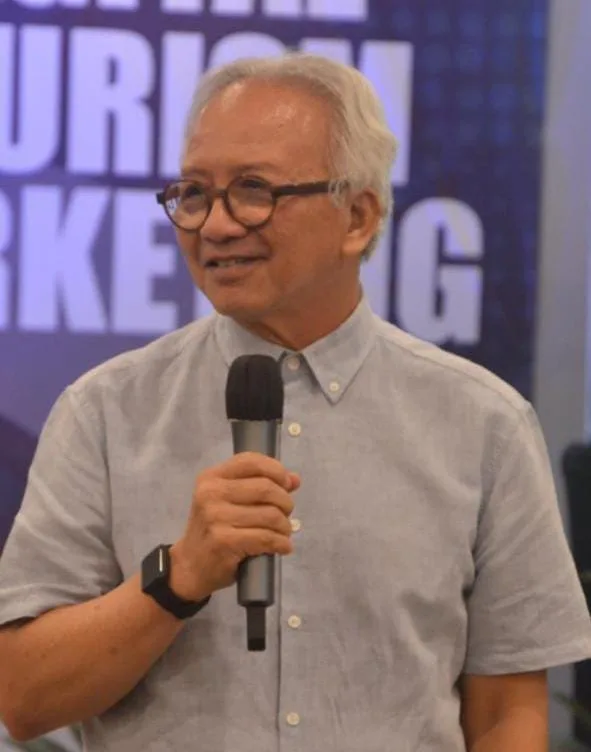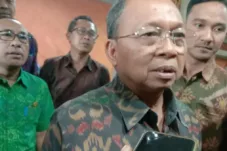Pariwisata berkelanjutan merupakan topik populer pada era sekarang (Branwell & Lane, 2005; Lu & Nepal, 2009; Ruhanen et al., 2015). Seiring meningkatnya perhatian global terhadap pemanasan global, perubahan iklim, dan fenomena overtourism, tren pariwisata berkelanjutan semakin mengemuka (Swarbrooke, 2011). Hal ini semakin diperkuat dengan adanya Resolusi Majelis Umum PBB 70/193 yang menetapkan International Year of Sustainable Tourism for Development tahun 2017, serta pengalaman pandemi global 2019–2021 yang mendorong munculnya kesadaran untuk mengembangkan pariwisata yang lebih ramah lingkungan dan budaya.
Konteks Nasional
Di Indonesia, wacana pariwisata berkelanjutan telah berkembang sejalan dengan dinamika global. Sejak awal 1990-an, isu ini mulai dikenal di ranah akademik. Kajian pariwisata berkelanjutan di Indonesia dilakukan sejak periode tersebut (Wall, 1992; 1993), dan segera diikuti akademisi dalam negeri (Gunawan, 1997; Salim, 1995).
Pada akhir tahun 1992, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan UNDP, UNESCO, PATA, dan WTO menyelenggarakan konferensi internasional bertema Universal Tourism: Enriching or Degrading Culture? (Jafari & Nuryamti, 1993). Acara ini dihadiri sekitar 300 peserta dari 20 negara, dengan sustainable tourism sebagai salah satu bahasan utama. Inilah momentum awal diperkenalkannya konsep pariwisata berkelanjutan di Indonesia.
Landasan Hukum
Konsep pariwisata berkelanjutan tertuang dalam berbagai regulasi, antara lain:
-
UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Pasal 2).
-
UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH (Pasal 1 dan 3).
-
UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
-
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 262 Ayat 1).
-
PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010–2025 (Pasal 2, 35, 37, 38, 55).
-
Perpres No. 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan.
-
Permenpar RI No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
Gaung pariwisata berkelanjutan di tingkat pemerintah semakin terlihat sejak penyelenggaraan Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia pada 2017 (Kemenpar RI, 2017).
Tantangan Global
Meskipun perhatian besar telah diberikan, kajian empiris menunjukkan pariwisata global justru masih bergerak ke arah yang tidak berkelanjutan (Hall, 2011; Sharpley, 2020). Pertumbuhan perjalanan dalam satu dekade terakhir meningkatkan emisi karbon, sementara fenomena overtourism di Barcelona, Islandia, dan Venesia menunjukkan dampak negatif berupa keterasingan masyarakat lokal, turunnya kualitas pengalaman wisata, infrastruktur yang terbebani, kerusakan alam, hingga ancaman terhadap budaya dan warisan (WTTC & McKinsey, 2017).
Pandemi COVID-19 juga memengaruhi sektor pariwisata. Secara historis, pandemi mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan, meski sifatnya selektif. Dalam konteks pariwisata, COVID-19 menimbulkan reorientasi di beberapa wilayah, namun di tempat lain justru memperkuat kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Respons terhadap isu ini membutuhkan pendekatan global. Namun tanpa transformasi mendasar, peluang perubahan menyeluruh sistem pariwisata tetap terbatas (Hall et al., 2020).
Paradoks Pariwisata Berkelanjutan
Pariwisata berkelanjutan menghadirkan paradoks (Hall, 2011; Williams & Ponsford, 2009). Di satu sisi, keberhasilannya terlihat dari difusi konsep di kalangan industri, pemerintah, akademisi, dan pembuat kebijakan. Di sisi lain, kegagalannya tampak dari terus meningkatnya dampak lingkungan akibat aktivitas pariwisata (Hall, 2011).
Pemerintah Indonesia telah menetapkan keberlanjutan sebagai salah satu asas pembangunan (UU No. 10 Tahun 2009). Kini, komitmen ini ditegaskan kembali untuk menyesuaikan paradigma pembangunan pariwisata dengan tuntutan global (Sustainable Development | UNWTO, n.d.).
Namun, muncul pertanyaan: paradigma seperti apa yang ingin kita gunakan? Apakah supply-driven (Dávid, 2011; Tyler & Dangerfield, 1999)? Apakah market-based (Font & McCabe, 2017; Hardeman et al., 2017)? Apakah berlandaskan anthropocentrism atau ecocentrism (Fennell, 2014; Sheppard & Fennell, 2019)? Perbedaan filosofi di antara pemangku kepentingan bisa berakibat tujuan keberlanjutan sulit tercapai.
Demi keberlangsungan program pemerintah, paradigma pariwisata berkelanjutan yang dijalankan seyogianya selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, pariwisata berkelanjutan sering dipadukan dengan konsep quality tourism (Jennings et al., 2009; Jennings & Nickerson, 2006). Meski istilah ini belum memiliki definisi baku, beberapa negara seperti India, Kanada, Armenia, dan Selandia Baru telah mengadopsinya. Quality tourism erat kaitannya dengan service quality (SERVQUAL) yang dikembangkan A. Parasuraman et al. (1985, 1988, 1993) serta Zeithmal & Berry (1990), yang cenderung mengarah pada market-oriented tourism.
Implikasi bagi Indonesia
Dengan paradigma pariwisata berkelanjutan yang condong pada orientasi pasar, maka konsekuensinya adalah pengadopsian konsep competitiveness sebagaimana diperkenalkan World Economic Forum. Indeks ini mencakup empat subindeks, 14 pilar, dan 90 indikator.
Akhirnya, paradigma “baru” pariwisata berkelanjutan inilah yang seharusnya menjadi dasar pemikiran pemerintah (Kemenparekraf) untuk diterjemahkan dalam empat pilar pembangunan kepariwisataan sesuai amanat UU Kepariwisataan Pasal 7, yaitu:
-
Industri pariwisata.
-
Destinasi pariwisata.
-
Pemasaran.
-
Kelembagaan kepariwisataan.
Tentang Penulis:
-
Alumnus Dept. Hospitality & Tourism, University of Wisconsin, USA.
-
Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI (2002–2009).
-
Tenaga Ahli Gubernur Jambi.